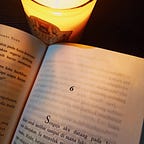Indonesia dalam Zaman Kolonial: "Indïe verloren, rampspoed geboren!" (Hindia hilang, kesengsaraan datang)
Oktober 2022 aku kembali ikut acara membaca dari Komunitas Baca Buku Sejarah Bareng. Untukku, mengikuti acara baca adalah hal yang nyenengin karena ada kesan punya teman baca. Juga, sering diadakan sesi ngobrol santai tentang buku bacaan masing-masing di Space Twitter.
Untuk Oktober kali ini tema acara baca yang telah ditentukan adalah Hindia Belanda pada masa kolonial. Aku tertarik dan suka banget sama pembabakan Indonesia ini. Jadi, dengan semangat aku bertekad membaca empat buku untuk sebulan. Secara tema besar sama, yaitu masa kolonial. Tapi, yang diceritakan sangat bervariasi.
Beberapa buku yang kubaca antara lain 1) Gadis Pantai karya Pramoedya Ananta Toer; 2) Student Hidjo karya Mas Marco Mardikusumo 3) Teh dan Pengkhianat karya Iksaka Banu; dan terakhir 4) Ras, Kuasa, dan Kekerasan Kolonial di Hindia Belanda 1805-1830 karya Peter Carey & Farish A. Noor.
Sesama penyuka buku-buku Hindia Belanda pada pembabakan kolonial pasti bisa ngerasain betapa serunya keempat buku di atas. Karena emang iya! Barisan buku yang keren banget, buah karya para penulis yang mengagumkan.
Berikut aku pengin bicara banyak tentang ketiga buku fiksinya. Yang terakhir nanti dulu. Bisa panjang banget soalnya tulisan ini, hahaha.
Dimulai dari ... latar suara ombak yang saling berkeriau, dan desau angin meniup pohon-pohon sepanjang pantai dan atap-atap sirap perkampungan nelayan. Sedang bau amis dan asin laut melayang-layang di udara untuk kemudian dinikmati oleh seorang gadis berumur empat belas tahun dengan sebutan Gadis Pantai. Terduduk di pelataran rumah kayunya, memandang laut yang menghidupinya dengan segala isi kandungannya dari kejauhan ...
1. Gadis Pantai, Pramoedya Ananta Toer (PAT)
"Kita ini biar hidup dua belas kali di dunia, tidak bisa kumpulkan duit buat beli barang-barang yang terdapat dalam hanya satu kamar orang-orang kota. Laut, memang luas, tak dapat terkuras, kaya tiada berbatas, tapi kerja kita yang memang hina tak berharga. Besok kau mulai tinggal di kota, 'nduk, jadi bini seorang pembesar. Kau cuma buka mulut, dan semua kau maui akan berbaris datang kepadamu...."
"Ah Bapak. Bapak. Itulah dunia yang kau tawarkan kepadaku, dunia serba gampang, cuma hati juga yang berat buat dibuka ... Aku tak butuhkan sesuatu dari dunia kota ini. Aku cuma butuhkan orang-orang tercinta, hati-hati yang terbuka, senyum tawa dan dunia tanpa duka, tanpa takut."
Roman ini punya beberapa unsur yang kusuka: kehidupan kolonial terutama rakyat kecil, dunia feodalisme Jawa, kehidupan kalangan priyayi, budaya patriarki, dan interaksi antar lapisan masyarakat yang berbeda. Sisi kolonialnya tidak terlalu menonjol, yang ditonjolkan adalah dunia foedalisme Jawa dan bagaimana ia berbentur dengan dunia lapisan masyarakat lain.
Aku jatuh cinta dengan segalanya dalam roman ini. Aku cinta dengan dunia kampung nelayan yang melingkupi kehidupan Gadis Pantai yang sederhana, gaya bercerita yang menyentuh batin Gadis pantai. PAT menyorot pada batiniah Gadis Pantai; kegusaran, kebingungannya, kemarahannya, keputusasaannya. Menyentuh gejolak batin gadis pantai, dan sering aku terguncang, ikut larut.
Gadis Pantai berkisah seorang gadis berusia 14 tahun dari perkampungan nelayan yang diambil sebagai istri percobaan oleh seorang bangsawan Jawa beragama Islam di kota Rembang pada awal abad ke-20. Gadis Pantai yang tidak mengenal ajaran islam, di dunia barunya atas perintah bendoro ia belajar mengaji dan sembahyang. Bendoro diceritakan sosok yang imannya kuat, alim. Tapi, justru ia mengambil seorang gadis yang belum menstruasi untuk dijadikan istri percobaan.
Menjijikan. Itulah yang dapat diperbuat dengan kekuasaan, harta, dan kedudukan (derajat).
Dari pembuka roman saja aku sudah terguncang. Gadis Pantai harus berpindah 'dunia'. Ia berangkat ke kota, bedaptasi dengan dunia baru, sebuah tempat tinggal di kota yang berdinding putih, megah, dinding yang dingin dan apatis terhadap penderitaan batinnya.
Kehidupannya sangat berubah. Ia terpisah dari Emak dan Bapak, hubungan anak-orang tua tak seperti dulu lagi karena derajat dirinya menjadi lebih tinggi. Ia sekarang adalah istri dari seorang bendoro (priyayi). Bujang wanita tua yang mendampinginya mengatakan hal yang menyakitkan.
"Mas Nganten bisa usir bapak Mas Nganten dari kamar."
Gadis Pantai telah bertitel Mas Nganten. Sebagai wanita yang berderajat tinggi di kediaman itu ia hanya melakukan dua hal, yaitu 1) memerintah bujang (pembantu) dan; 2) mematuhi segala perintah Bendoro (suaminya).
Tentang ini ada satu kutipan antara Gadis Pantai dengan Mbok atau bujang wanita tua yang selalu mendampingi dan melayaninya.
"Ah, Mas Nganten, di kota, barangkali di semua kota- dunia kepunyaan lelaki. Barangkali di kampung nelayan tidak. Di kota perempuan berada dalam dunia yang dipunyai lelaki, Mas Nganten."
"Lantas apa yang dipunyai perempuan kota?"
"Tak punya apa-apa, Mas Nganten. Kecuali..."
"Ya?"
"Kewajiban menjaga setiap milik lelaki."
"Lantas milik perempuan itu sendiri apa?"
"Tidak ada, Mas Nganten. Dia sendiri milik lelaki."
(Hal. 87-88)
Ruang gerak Gadis Pantai telah terkungkung, dan dirinya sebagai individu, manusia utuh yang memiliki dirinya sendiri, sudah tak berlaku lagi. Ia merindukan pergaulan di kampung nelayan yang tak mengenal derajat, tinggi rendah nilai manusia. Di sana, semua orang sama bekerjanya.
Di bagian ketiga dan keempat sangat mengguncangku. Berbagai konflik mengenai dalam kediaman dan di kampung halaman Gadis Pantai terjadi. Pada akhirnya, Gadis Pantai diusir oleh Bendoro setelah tiga bulan melahirkan anak perempuan. Ia angkat kaki dengan perintah meninggalkan bayi itu. Bagian ini bikinku sangat lara.
Betul yang dikatakan: “Gadis Pantai menusuk foedalisme Jawa yang tak memiliki adab, dan jiwa kemanusiaan tepat langsung di jantungnya yang paling dalam”.
Pengalaman membaca Gadis Pantai sangat kunikmati. Biar aku tenggelam berkali-kali. Biar aku tak akan pernah dapat membaca jilid selanjutnya.
2. Student Hidjo, Mas Marco Mardikusumo
Buku ini masuk dalam daftar sastra Indonesia yang ingin kubaca. Suasana membaca “Student Hidjo” seperti ketika aku menikmati buku-buku Balai Pustaka dulu. Bahasa melayu-nya bikin senyam-senyum, hahaha.
“Student Hidjo” pertama diterbitkan tahun 1918 dalam bentuk serial di harian Sinar Hindia. Penulis menjadi editor di sana. Pada 1919, cerita ini kemudian dijadikan buku dan diterbitkan oleh Masman & Stroink, perusahaan asal Semarang.
Awalnya kukira novel ini menitikberatkan pada kompleksitas dan pertentangan dalam kehidupan kolonial. Ternyata, "Student Hidjo" adalah cerita yang adem ayem yang mengangkat tema percintaan antara priyayi Jawa, yang kehidupannya sejuk dan damai, tak kekurangan sesuatu apa. Sepanjang membaca, aku mendapat kesan dunia priyayi Jawa ini tak tersentuh. Oleh apa? Oleh dunia lain. Dunia Bumiputera yang menghadapi sengsara dan kekurangan dalam segala-galanya, yang terpinggirkan dalam politik kolonial. Dunia yang tak terjamah kekerasan dan kepahitan kolonialisme.
Di novel ini, tak ada benturan yang berarti antara tokoh-tokohnya, antara kalangan bumiputera dengan Eropa/Belanda. Mereka menjalani hidup masing-masing tanpa konflik. Tapi, mengingat buku ini terbit 1919 dan di dalamnya terdapat pembicaraan tentang ketimpangan dalam berbagai hal antara Bumiputera dan orang-orang Eropa, bagaimana yang satu begitu merasa tinggi dari yang lain, ketakutan Bumiputera terhadap Bangsa Belanda dianggap sebagai bangsa tinggi dan patut dihormati, tentang pandangan kolot orang Belanda mengenai orang Jawa dan Hindia pada umumnya, dan mengingatkan bahwa pembaca untuk mengenang bahwa bangsa Belanda memang pada faktanya hampir mengeruk segala yang ada di tanah Hindia.
Mereka, orang-orang Belanda sebagai pendatang di tanah jajahan, kebanyakan tidak punya banyak pengetahuan tentang Hindia Belanda. Bangsa Belanda tidak tahu keadaan di Hindia, dan mereka pada zaman kompeni hanya bermaksud mencari uang semata, dimana mereka tak mengenal penduduk Hindia. Mereka hanya kenal sanak saudara di Hindia yang biasanya mengepalai pabriek yang mengetahui sedikit tentang Hindia. Jadi, mereka hanya mengenal tempat tinggal sekitar saudara mereka dan pabrieknya.
Juga vergadering Sarekat Islam pada tahun 1913 muncul dalam novel ini. Pencapaian yang mengagumkan.
Novel ini menyentuh ranah kehidupan priyayi yang memiliki posisi tawar tinggi dalam struktur masyarakat Hindia Belanda. Raden Hidjo adalah seorang pemuda bumiputera lulusan Hogere Burger School (HBS). Setelah lulus dengan dorongan orang tuanya Hidjo melanjutkan sekolah ke Delft, Belanda, untuk belajar teknik. Hidjo pergi meninggalkan tunangannya, Raden Ajeng Biroe, anak dari Bupati Jarak. Kedua keluarga ini sudah mengenal sangat lama satu sama lain dan berhubungan baik. Bahkan, mengikat anak masing-masing dalam pertunangan. Surprise, Raden Ajeng Biroe usianya baru 14 tahun saat Hidjo mau berangkat ke Delft, sementara Hidjo 18 tahun.
Keluarga Hidjo berasal dari Semarang, Jawa Tengah. Keluarganya bergelar Raden Mas, kalangan priyayi. Ayahnya Raden Mas Potronoyo merupakan seorang pengusaha. Hidjo bertunangan dengan R.A. Biroe, yang datang dari keluarga regent (bupati) di Jarak , sesuai keinginan ayahnya. Tapi, keadaan ini berubah ketika Hidjo telah pergi ke Belanda. Awalnya, Hidjo bertekad untuk tak tergoda gadis-gadis Belanda. Ia ingin belajar sungguh-sungguh, mengejar mimpi menjadi seorang ingenieur (insinyur), kemudian kembali ke Hindia Belanda.
Itulah juga yang kusemogakan. Ternyata Hidjo tergoda juga. Di bagian yang menceritakan affair antara Hidjo dan Betje aku sungguh tercegang sama kemerosotan idealisme-nya Hidjo. Lambat laun ia mulai melihat persamaan dirinya dengan sosok Faust dalam pertunjukkan drama Goethe yang ditontonnya bersama Betje, seorang perempuan Belanda nak pemilik rumah yang ditumpanginya selama bersekolah di Belanda.
Dan, akhirnya memang begitu. Hidjo, oh, Hidjo. Ambruk kamu di Delft, ya. Terjerat dalam godaan percintaan dan kesenangan di tanah yang bukan negerimu.
Hampir tidak ada adegan-adegan progresif selama Hidjo di Belanda. Sekembalinya ke Hindia Belanda ia batal dikawinkan dengan R.A. Biroe, pasangannya diganti dengan R.A. Woengoe. Sementara itu, R.A. Biroe bersama R.M. Wardoyo, kakak laki-laki R.A. Woengoe. Bagian inilah yang bikinku terheran-heran. Keempat pihak menerima begitu saja keputusan itu. Percintaan para priyayi ini sepanjang buku terasa datar, dan pada akhirnya, berakhir anti-klimaks.
Tapi, tak apa. Aku menikmati membaca buku ini. Aku puas dan senang banget berkesempatan membaca “Student Hidjo” yang kutemukan secara tak terduga di perpustakaan yang sering kukunjungi. Sebagai bacaan awal-awal abad ke-20, buku ini memberiku sedikit pengetahuan tentang keadaan masyarakat Hindia pada masa kolonial.
3. Teh dan Pengkhianat, Iksaka Banu
"Indïe/Indisch verloren, rampspoed geboren" adalah ungkapan populer yang digemakan lagi oleh pers Belanda pada awal dasawarsa 1940-an yang berarti "Hindia hilang, kesengsaraan datang". Ungkapan ini menyiratkan ketergantungan bangsa Belanda kepada Hindia. Mereka menganggap jika Hindia lepas, sumber utama perekonomian mereka akan hilang dan menyebabkan Belanda jatuh ke dalam kubangan kemiskinan. Kepercayaan ini terus melekat dan akhirnya menjadi mitos tersendiri dalam masyarakat Belanda yang tengah dirundung kegelisahan pascaperang.
Seperti yang sudah kutulis di atas, bangsa Belanda pada zaman kolonial kebanyakan datang ke Hindia Belanda untuk mendapatkan kehidupan yang lebih nyaman, ekonomi yang stabil, membangun karier masing-masing. Dalam buku "Ras, Kuasa, dan Kekerasan Kolonial di Hindia Belanda 1805-1830" tertulis:
"Segala macam orang-orang yang ingin mengadu nasib, yang tidak ada orang yang tahu sebelumnya mereka mengerjakan apa.”
Nilai ekonomis Hindia bagi negeri Belanda sangat besar. Lihatlah, tanah yang luas dan subur, yang kaya akan keragaman hayati dan non-hayati. Roda perekonomian dan keberlangsungan bangsa Belanda di vaderland dan di Hindia terutama bergantung pada apa yang mereka kerjakan dan berhasil rampas dari tanah jajahan. Jika Hindia terlepas, maka Belanda akan jatuh miskin, kehilangan pemasukan besar.
Dalam Teh dan Pengkhianat, terdapat 13 cerita pendek yang mengisahkan kehidupan bangsa Belanda di Hindia selama zaman kolonial. Alur waktu yang panjang terentang dari peristiwa direbutnya Kepulauan Banda oleh VOC dan peristiwa pembantaian Banda pada 1621 sampai dengan Desember 1957, satu dekade setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kumcer ini ditutup dengan cerpen berlatarkan peristiwa repatriasi Peranakan Belanda yang dalam tiga gelombang sejak 1949 meninggalkan tanah jajahan nenek moyangnya, tempat mereka lahir dan tumbuh bersama Bumiputera yang mereka panggil dengan sebutan menghina "Inlander". Kejayaan pada akhirnya menghilir pada kejatuhan, kekalahan.
Cerpen-cerpen berlatar zaman kolonial karya Iksaka Banu punya daya tarik tersendiri untukku, terutama karena aku suka diajak menyusuri sejarah lewat penceritaan yang membuat imajinasiku menyala, dan hanyut dalam peristiwa. 13 cerpen dengan latar sejarah dan isu yang berbeda-beda. Lewat sudut pandang orang Belanda kita melisik kehidupan, dan bertemu tokoh-tokoh Bumiputera hebat pada masa kolonial seperti Karaeng Pattingalloang, dan Ruhana Kudus. Aku selalu mendapatkan pelajaran sejarah di setiap judulnya, yang membuatku terpukau. Sering aku membaca dengan kacamata penulis, aku memperhatikan cara khas Iksaka Banu memperkenalkan latar sejarahnya, yaitu berat di dialog. Aku merasa dengan itu latar bisa mudah diikuti.
Isu dan latar sejarah yang diangkat menarik dan beragam banget. Dari Pembantaian Orang-orang Kaya Banda, pemberontakan di perkebunan teh oleh orang-orang Cina Makau dari Sindangkasih dan kedua dari Wanayasa, wabah cacar di Bali pada 1817, zaman kala Jepang menduduki Indonesia, dan warga Belanda banyak yang mengungsi kebanyakan ke Australia dan mereka juga memboyong bersama 10 ribu Bumiputra, sampai usainya perjanjian Renville 1948.
Kalau diurutkan, beberapa cerpen yang kusuka yaitu: 1) Kalabaka, 2) Kutukan Lara Ireng, 3) Teh dan Pengkhianat, 4) Sebutir Peluru Saja.
Kutukan Lara Ireng berkisah kecanduan opium yang bagai penyakit hitam yang terus merayu, dan membuat orang tak berhenti jatuh cinta, seperti kepada seorang wanita. Bumiputra buruh harian biasanya mengisap candu murah yang dicampur daun awar-awar, gula, sari jeruk di kedai yang remang. Aku suka banget bab opium ini. Aku belajar tentang opium di masa koloniali: distribusi opium oleh pemerintah yang dilaksanakan melalui lelang, opium seludupan, juga opium murah saingan opium pemerintah.
Seru-seru judul yang ada di kumcer "Teh dan Pengkhianat" ini. Karya Iksaka Banu adalah yang pertama bagiku dalam konteks membaca fiksi sejarah kolonial dalam sudut pandang Belanda.
Selesai! Buku-buku keren yang sangat layak untuk dibaca. Tak hanya dapat menikmati bukunya sebagai sastra, aku juga belajar banyak tentang kehidupan Indonesia pada babak kolonial.