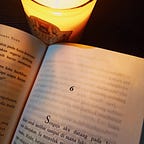Perkebunan Masa Kolonial hingga Revolusi Sosial di Tanah Deli (Bagian I)
Di artikel yang terbagi menjadi dua bagian ini aku ingin bercerita tentang dua buku nonfiksi bertema wilayah Sumatra Timur yang kubaca di bulan Maret.
Dari kedua nonfiksi ini aku menemui kesamaan topik yaitu perkebunan di Sumatra Timur menjelang dasawarsa akhir abad ke-19 sampai pertengahan abad ke-20. Topik yang menarik, karena perkembangan perkebunan yang pesat disusul dengan berdirinya perusahaan-perusahaan perkebunan raksasa yang didominasi orang Eropa berdampak pada berubahnya struktur sosial-politik yang signifikan di Sumatra Timur, puncaknya adalah revolusi sosial terhadap raja-raja di Simalungun pada pertengahan abad ke-20.
Artikel ini membahas buku pertama tentang perkebunan di Deli yang kubaca berjudul Jejak Planters di Tanah Deli: Dinamika Perkebunan di Sumatra Timur (1863-1996) karya Dr. Mohammad Abdul Ghani.
Kehidupan Sosial Kuli Kontrak
Aku tertarik dengan cerita-cerita perkebunan di Deli pada masa kolonial. Perhatianku yang paling besar adalah pada pergundikan di perkebunan, baik oleh pejabat-pejabat Eropa maupun kuli perkebunan itu sendiri, dan penderitaan para kuli perkebunan. Berikut aku akan menguraikan situasi setelah dibukanya perkebunan di Deli.
Singkatnya, perkebunan di Deli dibuka besar-besaran pada 1860-an setelah Jacobus Niewhuijs berhasil menghasilkan tembakau pembungkus cerutu bermutu tinggi di atas konsesi tanah cuma-cuma dari Sultan Deli, yang kemudian menarik para investor perusahan besar untuk menanamkan modalnya pada perkebunan.
Hal ini dorong oleh 1) terbitnya UU Agraria 1870 yang membuka sumber daya alam Hindia Belanda bagi kepentingan model negara induk, antara lain liberalisme penanaman modal asing dan pengizinan konsensi kuasa tanah selama 75 tahun lamanya kepada investor, serta kebutuhan dunia industri akan bahan baku, dan 2) intervensi raja-raja di Deli yang menandatangani izin konsesi tanah untuk kemudian dijadikan lahan perkebunan oleh para pemilik perusahaan Eropa.
Menurut hukum yang berlaku saat itu, tanah di Deli adalah milik para raja sepenuhnya, sehingga rakyat hanya meminjam tanah dari raja dan membayar pajak, kerja rodi bagi rakyat yang tidak mampu. Permasalahan tanah ini menjadi salah satu penyebab revolusi sosial di Simalungun yang akan aku bahas di bagian kedua.
Diketahui komoditas yang ditanam, di Deli pada abad ke-19 antara lain tembakau, karet, kelapa sawit, dan teh. Perusahaan besar membutuhkan banyak kuli untuk membangun dan mengerjakan perkebunannya. Namun, penduduk sekitar tidak tertarik bekerja sebagai kuli karena mereka mempunyai perkebunan sendiri dan tidak cocok dengan kultur perkebunan.
Maka, perusahaan mula-mula pada 1884-1900 merekrut orang-orang Cina dari Semenanjung Malaya (jajahan Inggris), kemudian seiring dengan berkembangnya perkebunan, didatangkan pula orang-orang Jawa.
Orang-orang Jawa tertarik dengan kemakmuran yang dijanjikan akan didapatkan di tanah Deli. Kemudian, akibat pengutamaan komoditas gula di Jawa, lahan padi menjadi berkurang dan terjadi kekurangan pangan.
Orang-orang Jawa ini menjadi kuli kontrak selama tiga tahun. Setelah kontrak berakhir, kuli dapat kembali ke tanah asal dengan biaya dibebankan kepada perusahaan, atau memperpanjang kontrak. Sebagian besar memilih opsi kedua karena terikat oleh utang judi sebagaimana dikutip dari Dari Penjara ke Penjara oleh Tan Malaka hal. 68:
“Kekurangan dalam segala-galanya menimbulkan keinginan untuk mengadu nasib dengan bermain judi, nafsu yang sengaja diciptakan oleh maskapai sesudah hari gajian. Yang kalah berjudi biasanya lebih banyak yang kalah daripada yang menang diizinkan berutang. Karena terikat utang, maka 90 dari 100 kuli yang habis masa kontraknya terpaksa memperpanjang kontraknya lagi. Utang menimbulkan keinginan berjudi dan perjudian menambah utang terus-menerus.”
Ini merupakan siasat pengusaha untuk menahan kuli-kuli agar setia pada perusahaan. Ketika hari gajian tiba, pada malam harinya digelar serangkaian hiburan seperti pertunjukkan wayang. Hiburan ini dibatasi hanya untuk masa panen, dan disediakan bangsal khusus untuk itu. Pada hari seperti ini, kuli biasanya berjudi atau pergi ke tempat pelacuran. Cara ini ampuh menguras kantong kuli yang baru saja terisi.
Pergundikan dan Pelacuran
Pada 1875 para buruh-buruh perempuan pribumi direkrut dalam skala besar. Selain untuk memenuhi kebutuhan kuli perkebunan. Mereka dipekerjakan untuk menggaru tanah, menyortir, memilah, menggantung, hingga mencari ulat tembakau. Mereka juga dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan seksual para pejabat-pejabat dan kuli perkebunan agar betah.
Mayoritas buruh perempuan didatangkan dari Jawa berasal dari kelompok masyarakat yang miskin, mereka didatangkan dalam kondisi belum menikah dan ditipu akan memiliki penghasilan tinggi. Begitu tiba, para kuli perempuan langsung diperiksa di sebuah kamar kecil di kantor perkebunan. Para pegawai Eropa berkulih putih mendapat kesempatan pertama memilih kuli perempuan yang baru tiba. Kuli yang dianggap paling menawan kemudian diambil menjadi gundik pengawas perkebunan.
Praktik pergundikan ini sangat didukung oleh directuur, puncuk jabatan di perkebunan. Pegawai kulit putih disarankan memiliki gundik agar terbebas dari pekerjaan rumah selepas bekerja dan memenuhi kebutuhan seksual.
Para kuli perempuan terpilih tak punya daya untuk menolak, karena penolakandianggap sebagai sikap membangkang yang berujung pada dikenakannya siksaan.
Hubungan antara pejabat kulit putih yang menduduki stratifikasi tertinggi dengan kuli rendahan ini menciptakan relasi ketertindasan yang berlapis. Di tangan orang-orang Eropa, para gundik menjadi korban kesewenang-wenangan tuan kebun.
Tuan Kebun biasanya adalah seorang lelaki muda berperangai kasar dan agresif. Selanjutnya, hubungan homoseksual yang jamak di perkebunan membuat mereka merasa perlu menegaskan maskulinitas dan preferensi heteroseksual mereka dengan cara bersikap kasar dan hidup bersama perempuan gundik.
Para kuli perempuan yang dijadikan gundik terbebas dari status kuli, mereka pun tidak lagi kekurangan makan akibat upah yang amat kecil. Upah kuli perempuan rata-rata dua setengah gulden per bulan atau delapan sen per hari, sementara makan warung di perkebunan menghabiskan 15 sen. Hal ini diperparah dengan terdapat aturan para kuli perempuan tidak akan mendapat upah jika tidak bekerja di beberapa perkebunan, pengawas perkebunan menentukan kapan si kuli perempuan bekerja, dan larangan mencari penghasilan tambahan di luar perkebunan. Sistem yang mencekik ini membuat para kuli perempuan pada umumnya tidak mampu bertahan hidup. Mereka dihadapkan pada pilihan terbatas: tetap menjadi kuli perkebunan dengan upah yang sangat sedikit atau memperoleh penghasilan tambahan dengan melacurkan diri.
Praktik pelacuran pada awalnya dimulai untuk meredakan praktik homoseksual yang merajalela di kalangan kuli pada tahun-tahun pertama perkebunan dibuka. Diketahui pelopor praktik ini adalah kuli kontrak dari Cina, yang mengakibatkan banyak perkelahian, yang bahkan berujung pada pembunuhan, serta merebaknya penyakit seksual. Praktik ini kemudian bertujuan sebagai pemikat kuli laki-laki agar betah di perkebunan.
Praktik pelacuran difasilitasi oleh perusahaan dengan membangun tenda-tenda di tanah-tanah kosong perkebunan. Kuli perempuan terpaksa melacurkan diri karena harus bertahan hidup. Mereka hanya menerima upah 1,5 gulden sebulan, setengah dari pendapatan pekerja laki-laki dan tidak mendapat tempat penampungan.
Pelacuran terjadi pada setiap malam gajian. Saat itu kuli perempuan akan berdandan cantik dan menjadi penari ronggeng. Bisnis ini dijalankan oleh germo yang memiliki jabatan mandor besar (ploeg baas) asal Jawa yang berperan juga sebagai pemimpin kelompok ronggeng. Praktik pelacuran dimulai setelah pertunjukkan ronggeng.
Dampak dari praktik ini adalah menyebarnya penyakit kelamin di perkebunan, dan maraknya kelahiran anak-anak di luar nikah. Namun, para pemilik perkebunan diuntungkan dalam hal ini karena tidak perlu melakukan perekrutan kuli-kuli baru yang memakan ongkos besar.
Koelie Ordinantie dan Gerakan Radikal
Diperkenalkanya Koelie Ordinantie (1880) adalah untuk mengatur para kuli yang jumlahnya ratusan ribu. Dalam ordonansi ini terdapat butir-butir hukuman yang dikenal dengan ponale sanctie (saksi pidana) antara lain sebagai berikut; Melanggar kontrak dikenakan denda, aatau penjara. Lari dari pekerjaan akan ditangkap kembali, dihukum rotan, atau dirantai. Malas bekerja dikenakan pidana karena dianggap pelanggaran UU. Menolak pekerjaan akan dibebankan kerja paksa selama setahun. Terakhir, jika ada perlawanan atau permusuhan maka yang bersangkutan akan didenda sebesar 100 gulden.
Meloncat ke periode setelah kolonial, keamanan negara yang merosot serta berbagai kekacauan sosial yang terjadi pada periode 1945-1965 adalah momen puncak bagi petani penggarap dan mantan kuli perkebunan untuk mengkosolidasi diri dan mulai muncul gerakan untuk mempertahankan lahan agar tidak diambil oleh pemilik sebelumnya yang sah.
Diketahui beberapa faktor munculnya gerakan radikal di perkebunan adalah sebagai berikut: 1) Realitas dominasi perkebunan di Sumatra Timur; 2) Sistem penguasaan lahan kebun oleh perusahan-perusahaan asing yang besar, 3) Stratifikasi sosial, 4) Disparitas sosial ekonomi dengan masyarakat sekitar, terakhir 5) Konflik penggarapan lahan konsensi yang belum selesai.
Terdapat dua peristiwa di perkebunan Sumatra Timur yang berkaitan dengan gerakan radikal. Pertama, Peristiwa Desa Perdamaian di Tanjung Morawa pada 16 Maret 1953. Kedua, Peristiwa Bandar Betsy di Simalungun pada 14 Mei 1965.
Artikel ini berlanjut ke bagian dua.